 |
Judul : Magnitudo 9
Penulis : Tim FAHIMA Jepang
Dan FLP Jepang
Penerbit : ABATASA Publishing
Tahun Terbit : 2011
|
Magnitudo 9 adalah sebuah buku
yang berisi kumpulan kisah inspiratif pasca bencana Jepang 2011. Jujur,
sebelumnya aku tidak terlalu tertarik untuk membaca buku ini. Kupikir, ah
paling isi bukunya tentang cerita-cerita menyedihkan orang-orang yang terkena
bencana. Kalau ditanya mengapa aku punya buku ini padahal tidak tertarik
membaca, itu karena aku dikasih langsung oleh salah satu penulisnya, mantan
anggota FLP Jepang.
Ketidaktertarikanku pada buku ini
(awalnya) mungkin karena aku tidak tahu betapa dahsyatnya bencana yang melanda
Jepang pada Maret 2011 tersebut. Bencana besar yang didominasi oleh gempa,
tsunami, dan kebocoran radiasi nuklir ini ternyata tidak sampai di telingaku
pada 3 tahun lalu. Yang kuingat saat itu aku hanya pernah mendengar isu radiasi
nuklir, sehingga harus berhati-hati saat terkena air hujan karena mungkin saja
air hujannya mengandung radiasi yang terbawa oleh awan. Tapi dulu itu aku tidak
tahu apa yang menjadi penyebabnya. Duh, katronya
aku dulu.
Setelah membaca buku ini, aku
merasa tambah kagum dengan Jepang. Bagaimana tidak, pada saat bencana, mereka
tidak terpuruk malah semangat mereka semakin kuat. Pada berita-berita di TV,
kesedihan masyarakatnya disorot sekilas, tapi tak ada gambar close up mayat atau lagu-lagu yang
menyayat. Nuansa yang dibangun adalah optimisme, seakan-akan mereka memberi
pesan bahwa “bencana ini memang dahsyat tapi kita pasti bisa bangkit”.
Beberapa penulis dalam buku ini
membandingkan suasana tersebut dengan apa yang terjadi di Indonesia saat gempa
dan tsunami Aceh pada tahun 2004. Media di Indonesia langsung memainkan
lagu-lagu sendunya Ebiet G. Ade dan mengekspos penderitaan para korban bencana.
Selain sikap setelah bencana,
pencegahan sebelum bencana antara Indonesia dan Jepang sangat berbeda. Terbukti
meskipun kekuatan gempanya hampir sama, yakni 9 magnitudo (sedangkan di Aceh 9,3
skala Richter) namun jumlah para korban yang meninggal sangat berbeda jauh. Pada
gempa di Aceh, jumlah korban sebanyak 230.000 yang meninggal sedangkan di Jepang
“hanya” sekitar 10.035.
Hal ini disebabkan oleh
pencegahan sebelum gempa yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Sejak kecil,
anak-anak di Jepang telah diajari bagaiaman menghadapi bencana, terutama gempa dan
tsunami karena Jepang sama seperti Indonesia terletak di Ring of Fire yaitu di antara 3 lempeng aktif (Lempeng Eurasia,
Lempeng Laut Filipina, dan Lempek Pasifik) yang masih berpotensi “bergejolak”. Simulasi
bencana dengan rutin dilakukan di sekolah atau pun instansi pemerintahan. Mereka
juga membuat tanggul penahan tsunami di bibir pantai. Meskipun pada akhirnya,
tanggul tersebut roboh diterjang tsunami, namun cukup berandil besar mengurangi
luasnya daerah yang tersapu tsunami. Bangunan-bangunan mereka pun sudah
dibangun sesuai untuk daerah yang rawan gempa. Keren sekali bukan?
Satu yang perlu kucatat dari buku
ini yaitu “100 tahun bahkan 1000 tahun merupakan rentang waktu yang pendek
dalam skala geologi”. Tercatat bahwa 1000 tahun yang lalu, gempa dan tsunami
serupa juga pernah terjadi di Jepang. Siklus alam selalu teratur. Oleh karena
itu, pesan penulis kita memiliki PR yang cukup berat yaitu meneruskan pesan ke
generasi penerus kita hingga ratusan bahkan ribuan tahun ke depan mengenai
potensi bencana ini.
Selain cerita penulis tentang apa
yang mereka alami saat bencana itu terjadi, buku ini juga memaparkan bagaimana
pendidikan gempa sejak kecil, pelajaran-pelajaran yang bisa mereka ambil dari
sikap bangsa Jepang setelah mengalami bencana, sejarah penanganan gempa dan
tsunami di Jepang, pemberian bantuan, dan bahkan mengenai panduan singkat penanganan
kegawatdaruratan dan tekanan psikologis pascabencana.
Buku ini sangat cocok dibaca bagi
Anda yang ingin mengais pelajaran dari bangsa Jepang yang tak pernah menyerah.







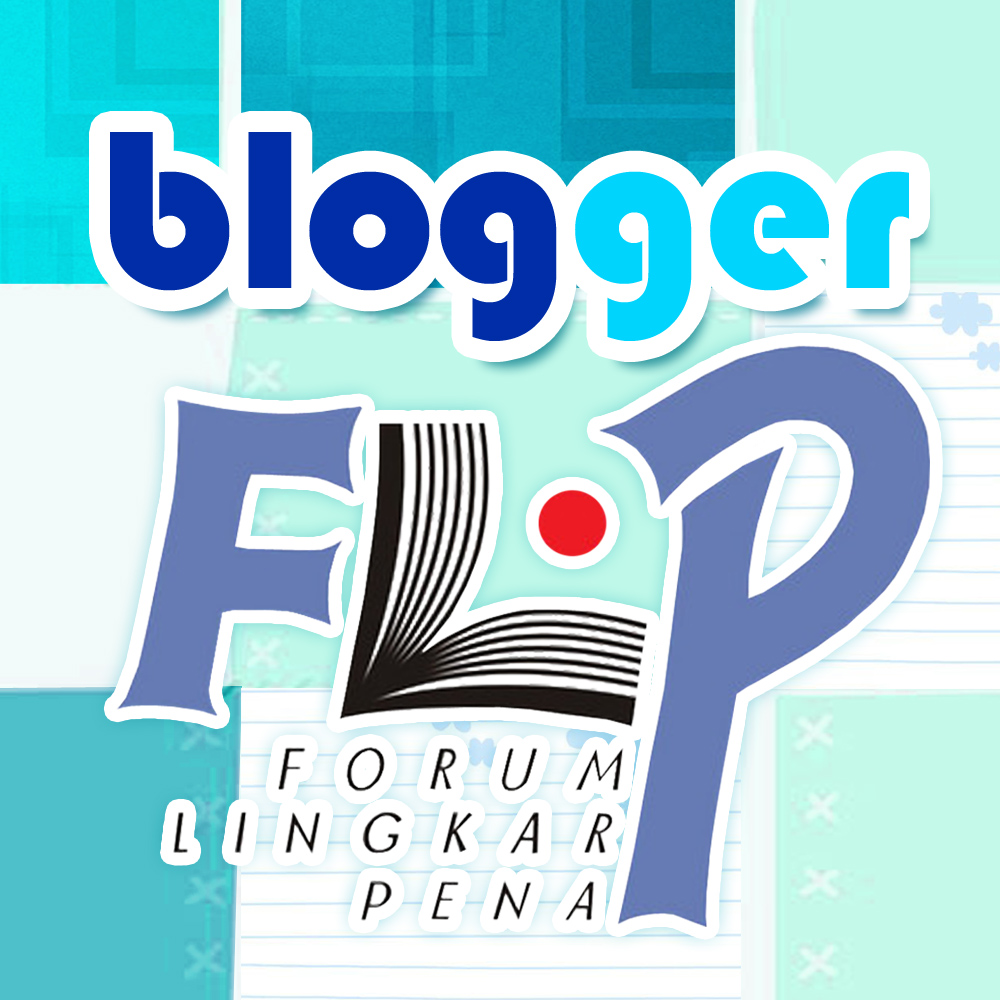


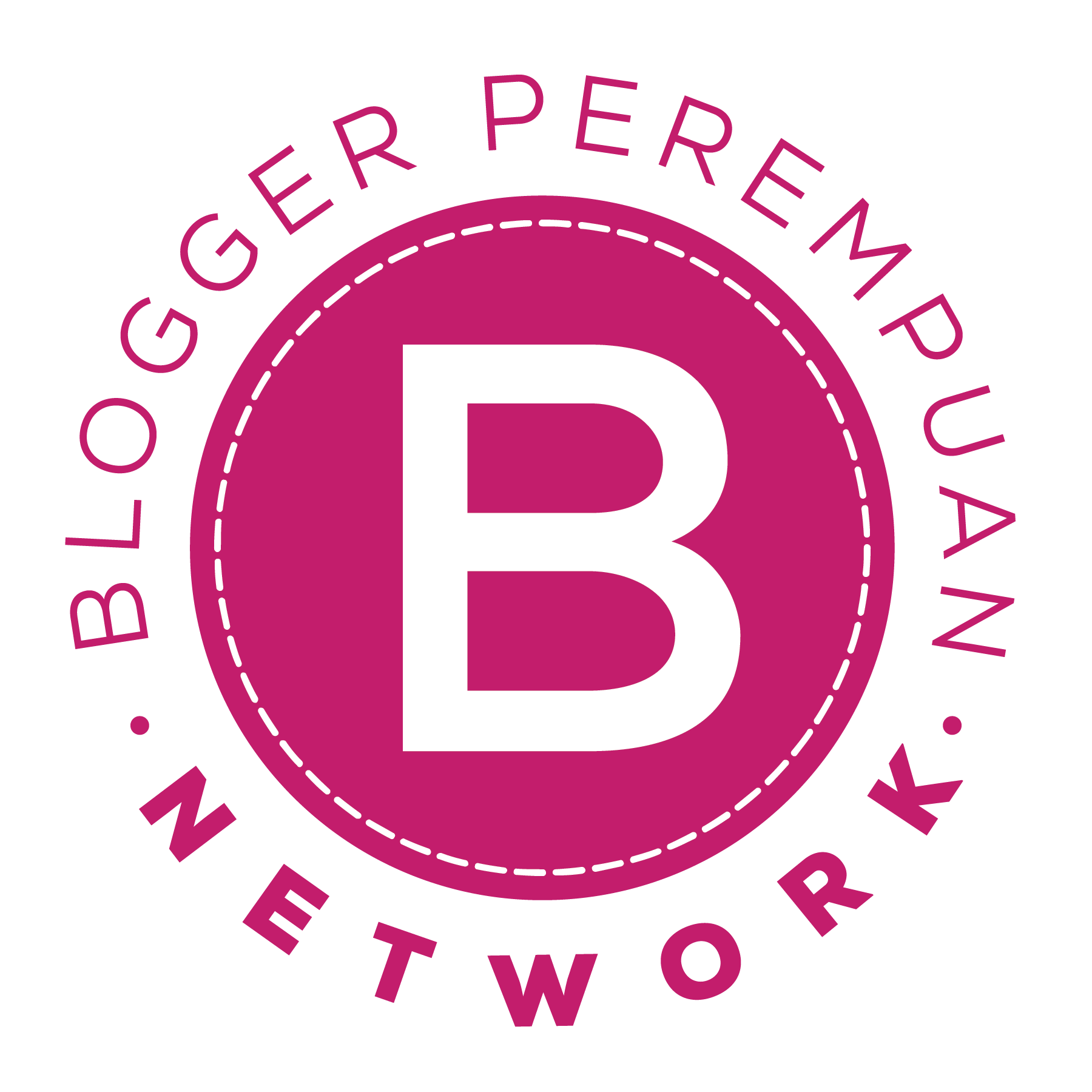
Posting Komentar
Posting Komentar