Tulisan ini merupakan kolaborasi antara curcol tentang keadaan chaos yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 sekarang dan review novel Hujan karya Tere Liye. Aku membaca bukunya sudah agak lama, berminggu-minggu yang lalu. Baru tergerak akan me-review-nya setelah ngerasa relate antara kondisi pandemi yang sepertinya tak akan pernah berakhir dengan cerita yang ada di novel Hujan ini. Btw, review novelnya penuh spoiler agar hubungan yang kumaksud dengan kondisi sekarang bisa terlihat lebih jelas.
Novel Hujan
Sekali lagi aku tercengang dengan isi cerita dari penulis yang sama, selalu mengesankan. Terlebih ketika pandemi Covid-19 terjadi, aku merasa seperti dibawa kembali ke tempat dan waktu di dalam novel Hujan. Mirip meski tak serupa. Isu besar yang diangkat dalam novel ini adalah perubahan iklim akibat ketidaksabaran manusia.
Alur maju mundur digunakan
pada novel ini. Berlatar ruangan kubus 16 meter persegi dengan segala peralatan
medis tercanggih, sang tokoh utama menceritakan seluruh kisahnya tentang hujan.
Bagaimana akhirnya si tokoh utama berakhir di ruangan tersebut bersama
paramedis senior untuk menjalani terapi penghapusan ingatan, itulah yang ia
ceritakan dalam 318 halaman. Isu pribadi yang dirasakan tokoh utama adalah
bagaimana cara melupakan hal-hal menyenangkan sekaligus menyakitkan dalam
hidup.
 |
Judul: Hujan
Penulis: Tere Liye
Penerbit: Gramedia
Lail dan Esok
Hal-hal penting dalam
kehidupan Lail selalu terjadi saat hujan, termasuk saat ia kehilangan ibunya
dan pertemuan pertamanya dengan Esok. Salah satu kenangan lain tentang hujan
yang berkesan bagi Lail adalah ketika Esok menyelamatkannya (lagi) dari hujan
asam. Hujan pertama yang terjadi setelah letusan gunung purba sangat berbahaya.
Kadar asamnya sangat pekat, sangat berbahaya bagi makhluk hidup dan bahkan
benda mati di permukaan bumi.
Untung Esok bisa membujuk
Lail untuk berteduh. Lail awalnya memberontak karena masih ingin berada di
dekat kejadian terkuburnya sang ibu. Esok membawanya bersepeda yang warna merahnya
langsung pudar setelah kena air hujan. Mereka berlindung di bawah rumah-rumahan
plastik berwarna oranye. Cukup membingungkan sebenarnya ketika semua rumah
permanen rubuh tak bersisa akibat gempa, rumah-rumahan plastik tetap kokoh
sebagai tempat berlindung.
Lail
menjadi yatim piatu setelah bencana alam berupa meletusnya gunung purba dan
gempa bumi yang diakibatkannya terjadi. Esok sendiri adalah satu-satunya anak
yang selamat dari 5 bersaudara yang akan berangkat ke sekolah. Beruntung, ibu
Esok masih bisa diselamatkan setelah tertimpa material bangunan karena ia
sedang ada di toko roti miliknya saat bencana terjadi.
Soke Bahtera, nama lengkap
Esok, adalah seorang pemuda genius yang berusia 2 tahun di atas Lail. Mereka
berdua bertemu di tempat kejadian dan menyaksikan sendiri bagaimana gempa bumi
menelan hidup-hidup tubuh keluarga yang mereka cintai. Sementara ibu Esok
dirawat di rumah sakit, mereka berdua tinggal di bekas stadion yang berfungsi
sebagai tenda pengungsian. Di tenda pengungsian, Esok dan Lail membantu para petugas,
marinir, dan relawan melakukan apa saja yang mereka bisa agar kehidupan bisa
berjalan dengan lebih normal. Kecerdasan Esok mulai terlihat saat itu, ia
membantu banyak hal dengan kegeniusannya, pun perhatiannya kepada Lail mulai
tampak.
“Aku tahu kenapa aku dipindahkan dari bagian mencuci ke memasak.” Lail terdiam, menatap celemek barunya, hadiah dari Esok. “Kamu yang meminta mereka agar aku dipindahkan, kan?” Ditanya begitu, Esok hanya nyengir, mengangkat bahu. (Hal 67)
Setahun kemudian setelah
bencana letusan gunung skala 8 VEI dan gempa bumi yang diakibatkannya, 8 pusat
pengungsian di kota mereka ditutup. Lail, seperti anak-anak lain yang
kehilangan seluruh keluarganya, akan pindah ke panti sosial. Esok dengan
keberuntungannya diangkat sebagai anak asuh di keluarga terpandang, Esok
menyetujuinya karena mengingat kondisi ibunya yang sering jatuh sakit sejak
bencana tersebut terjadi. Keluarga dermawan tersebut bersedia memberikan
fasilitas terbaik untuk menunjang kesehatan ibu Esok dan tentu saja membiayai
pendidikan Esok setinggi-tingginya.
Lail sedih karena mereka
harus berpisah, meski ternyata kesedihannya tersebut tidak seberapa dengan
kesedihannya ketika Esok harus tinggal di ibukota. Esok lulus sekolah dengan
begitu cepat dan menerima beasiswa super prestisius. Selama di ibukota, Esok
begitu sibuk. Terhitung, mungkin tidak sampai 5 kali pertemuan di novel ini
sesudah mereka berpisah. Catat, hanya ada dua kali panggilan telepon, itu pun
Esok yang menelepon. Lail seberapa pun inginnya, tak pernah menelepon lebih dahulu,
takut mengganggu Esok yang sedang mengerjakan proyek mesin raksasa.
Lail mengisi waktunya dengan
mengikuti kegiatan asrama di panti sosial yang super padat, sekolah,
mengunjungi toko kue ibu Esok yang dibangun kembali, serta mengikuti pelatihan
relawan. Maryam, sahabat sekamar Laili di asrama, sangat berperan penting di
masa-masa pengalihan perhatian Lail ini. Ia yang mengajak Lail ikut mendaftar
menjadi relawan, hingga mereka sukses menginspirasi relawan lainnya karena pada
suatu musibah mereka berhasil menyelamatkan warga satu kampung dari banjir
bandang dengan hampir mengorbankan nyawa mereka sendiri.
Sekolah sendiri tidak pernah
terlalu penting bagi Lail. Setiap kali Esok bertanya, bagaimana sekolah. Lail
akan menjawab, membosankan. Hingga pada suatu ketika Lail diterima di sekolah
perawat, saat itulah ia merasa sekolah menyenangkan dan itu sejalur dengan
kegiatan relawan yang selama ini ia ikuti.
Perubahan Iklim Dunia
Bukan hanya kehidupan Esok dan Lail yang berubah
sejak bencana besar itu datang, tapi juga kehidupan dunia. Anomali iklim terjadi.
Saat itu tahun 2050-an, segala jenis kecanggihan teknologi seolah dapat
melakukan apa saja untuk mengubah bumi. Masyarakat yang tinggal di negara 4
musim meminta para ilmuwan untuk melakukan rekayasa cuaca agar kondisi sosial
ekonomi yang terpengaruh oleh perubahan cuaca dapat pulih kembali.
KTT Perubahan Iklim Dunia berjalan dengan sangat
alot untuk memutuskan hal itu. Para ilmuwan, meskipun bisa, mereka memilih
untuk tidak melakukannya karena mereka tahun dampak buruk yang terjadi di masa
depan. Suara-suara keberatan dari negara tropis atas intervensi lapisan
stratosfer juga tidak diindahkan. Akhirnya karena desakan dan berbagai kepentingan
terus menekan, akhirnya koalisi negara-negara subtropis secara resmi melepaskan
8 pesawat ulang-alik, menyemprotkan gas anti sulfur oksida di lapisan
stratosfer. Bertahun-tahun kemudian, dampak buruknya dirasakan oleh
negara-negara tropis, termasuk negara Lail dan Esok.
Awalnya menyenangkan dapat melihat salju di tanah
yang biasanya hanya terjadi musim hujan dan kemarau. Namun ketika
bertahun-tahun hanya turun salju, warga negara tropis pun melakukan desakan
yang sama kepada para petinggi dan ilmuwan untuk kembali merekayasa cuaca di
langit negara tropis. Bentrokan terjadi dimana-mana akibat kegoyahan ekonomi
yang diakibatkan oleh nihilnya hasil pertanian akibat cuaca yang aneh.
Dengan memperhitungkan segala kemungkinan dan
mempersiapkan solusi, termasuk si mesin raksasa, para ilmuwan pun melakukannya
sekali lagi. Matahari kembali muncul, sebaliknya hingga berbulan-bulan kemudian
hujan tidak turun sama sekali. Lail yang terbiasa dengan hal-hal yang penting
saat hujan merasa kehilangan. Bumi hanya menunggu untuk hancur karena suhu
panas yang ada bisa membuat es di kutub menjadi lebih cepat serta hal-hal
destruktif lainnya akibat keseimbangan alam yang terganggu.
Lail yang khawatir bertanya pada Esok, bahkan bukan
hanya tentang kondisi cuaca mengkhawatirkan, juga banyak tentang kondisi
lainnya. Esok hanya berkata, teknologi selalu bisa mengatasi masalah apapun. Ya
ampun, Esok. Cool sekali.
Desakan-desakan Tak Sabar
Meski Esok berkata akan selalu ada jalan keluar
dari teknologi untuk mengatasi masalah dunia yang terjadi, tapi jika bisa
memilih tentu sebaiknya melakukan langkah pencegahan lebih baik sebelum terjadi
bencana akibat ketidaksabaran manusia. Pada kasus Lail dan Esok, seandainya
para warga bisa bersabar menunggu alam pulih dengan sendirinya, maka perubahan
iklim yang terlalu cepat dan ekstrem tidak akan terjadi. Alam selalu punya cara
untuk me-recovery diri sendiri. Gas
sulfur oksida yang dihasilkan oleh letusan gunung purba memang luar biasa
banyak sehingga butuh bertahun-tahun agar atmosfer bisa kembali normal.
Kondisi pelonggaran PSBB dan kenekatan banyak
orang yang mudik menjelang lebaran 2020 ini adalah contoh nyata aplikasi dari
ketidaksabaran yang sama. Efek jangka panjangnya mungkin tidak akan langsung
terasa, tapi tunggu saja jika tidak ada yang berubah. Bahkan semua yang tidak
ikut melakukan pun akan terkena dampaknya. Ekonomi bisa dipulihkan kembali
(atau mungkin kondisi the new normal
malah akan membuat sistem ekonomi yang baru akan menjadi lebih kuat di bidang
jaringan digital), tapi nyawa manusia tidak.
Pembukaan beberapa jalur transportasi umum oleh
pemerintah memang akan membuat celah yang bisa ditembus oleh otak-otak tanpa
empati. Kelesuan ekonomi secara nasional menjadi penyebab utama kebijakan
dengan banyak ‘tapi’ ini diputuskan. Persis seperti desakan-desakan tak sabar
dari warga negara Esok dan Lail. Langkah-langkah pencegahan memang akan terlihat
atau terdengar konyol sebelum kejadian. Jika sudah kejadian semua kena batunya,
tidak hanya menimpa orang yang menyebabkannya.
Mereka yang jengkel bahkan suudzon ada konspirasi herd
immunity di balik kebijakan ini. Bukan tidak mungkin, mekanisme herd immunity terjadi dalam kondisi chaos seperti ini. Memanfaatkan kegelisahan
orang-orang yang mulai bosan tinggal #dirumahaja, mereka yang tak peduli apapun
asal mudik, dan mirisnya mereka yang tetap terpaksa harus berkeliaran karena
desakan ekonomi, skenario herd immunity bisa
jadi ‘jalan keluar’ yang bodoh. Akan ada banyak orang yang harus ditumbalkan. Hitungan
kasar jika jumlah penduduk Indonesia berjumlah 267 juta jiwa, maka sebanyak 5% (hitungan
teoritis) yaitu 13 juta jiwa lebih akan berujung pada kematian. Tengok negara
Swedia yang mempraktikkan herd immunity ini.
Dengan skenario ini, pandemi memang akan lebih
cepat selesai. Tapi ketika semua orang terpapar virus corona dalam waktu yang
sama, sedang fasilitas dan tenaga medis kewalahan menanganinya, maka pilihannya
hanya ada 2. Bertahan atau mati. Mereka yang punya imunitas kuat akan bisa
sembuh, yang lemah akan meninggal. Mirip seperti seleksi alam di hutan rimba. Mengenaskan
sekali, kita manusia yang punya banyak kehidupan dan tautan dengan sekitar. Meninggal
dengan cara terpapar Covid-19 hanya akan membuat hidup rasanya sia-sia, belum
lagi luka yang tidak akan mudah sembuh di hati orang-orang terdekat. Harga yang
sangat mahal untuk sebuah kenekatan (atau ketidakpedulian?) yang tidak perlu.
Jangan tanyakan nasib tenaga kesehatan, hingga
sekarang saja sudah banyak yang berjatuhan. Bukan karena penanganan medis yang
lemah, tapi karena mereka kelelahan menghadapi lonjakan pasien. Dengan sistem
imunitas yang menurun akibat lelah dan paparan virus corona dari pasien yang
mereka tangani, mereka syahid dalam pandemi. Jika mereka sampai menyerah karena
#IndonesiaTerserah, maka kemana lagi kita akan menggantungkan nasib penanganan
kesehatan kita.
Pemusnahan Setengah Populasi Umat Manusia
Semua berawal dari bayi ke-sepuluh
milyar yang lahir pada hari pertama ajaran baru sekolah Lail dan Esok, 21 Mei 2042. Tayangan wawancara di
televisi dengan narasumber seorang profesor yang Lail lihat di dalam kapsul
kereta menyatakan bahwa dunia ini sudah terlalu sesak dengan umat manusia. Alam
punya cara sendiri untuk kembali menyeimbangkan jumlah populasi makhluk hidup
di atasnya.
Profesor itu berkata, “Umat
manusia sejatinya sama seperti virus. Mereka berkembang biak cepat menyedot
sumber daya hingga habis, kemudian tak ada lagi yang tersisa. Mereka rakus
sekali. Maka seperti virus, hanya obat yang paling keras yang bisa
menghentikannya. Saya tidak bicara soal perang, atau epidemi penyakit, itu
tidak pernah berhasil menghentikan umat manusia. Puluhan perang berlalu,
belasan wabah penyakit mematikan muncul, umat manusia justru tumbuh berlipat
ganda. Saya bicara tentang obat paling keras.” (Hal 16)
Bisa ditebak apa yang menjadi
obat paling keras dalam novel ini. Dan demi apa, saat aku mengedit bagian
terakhir tulisan ini, tanggal 21 Mei
2020, adalah tepat 22 tahun sebelum bencana besar tersebut akan terjadi. Skenario-Nya agar aku
merasa takjub dengan cara menyibukkan urusan-urusanku setelah mem-publish draft awal tulisan ini pada 2 hari sebelumnya.
Mungkinkah pandemi Covid-19 ini adalah salah satu cara semesta menyeimbangkan diri? Apakah ini obat paling keras versi 2020?
Apa yang akan dilakukan Esok
jika ia hidup sekarang? Jika kondisi bumi sudah tidak tertolong lagi ia dan
timnya membuat mesin terbang, apakah ia akan membuat mesin pemupuk empati dan
pemusnah kebodohan? Aku harap begitu. []






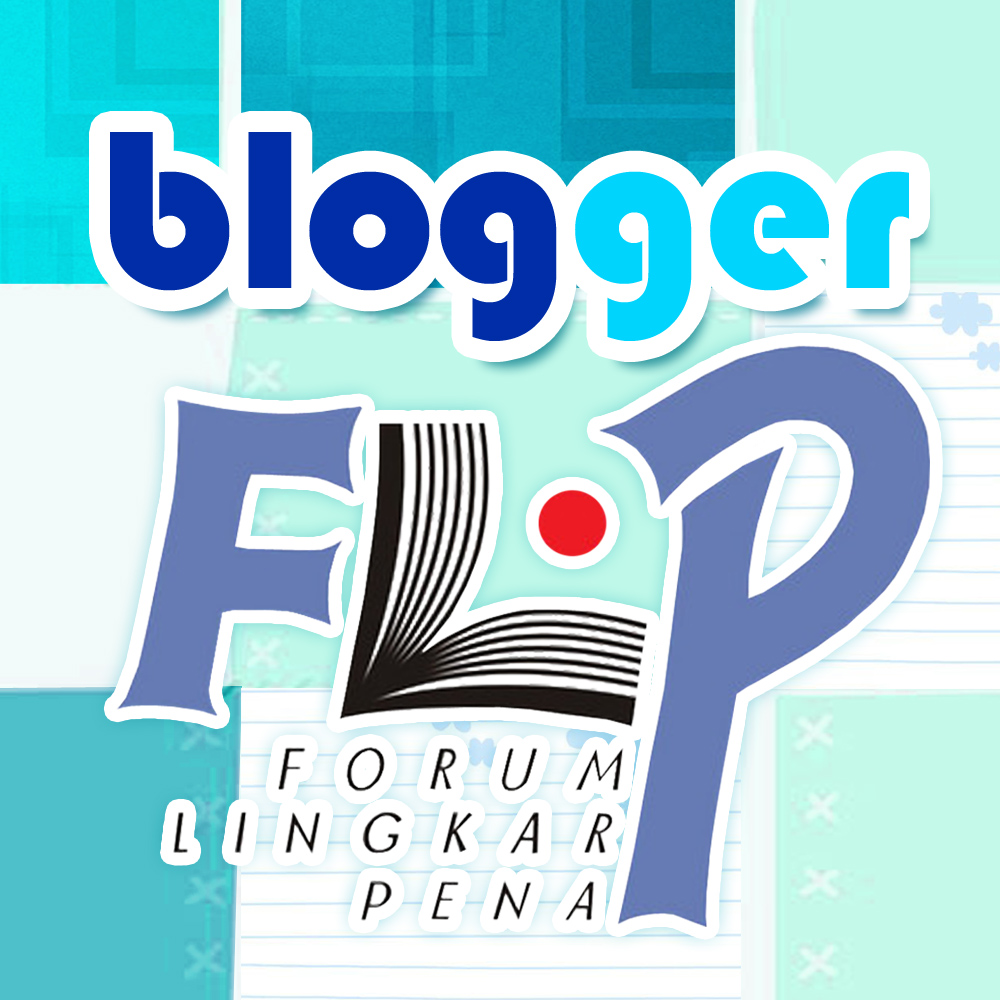


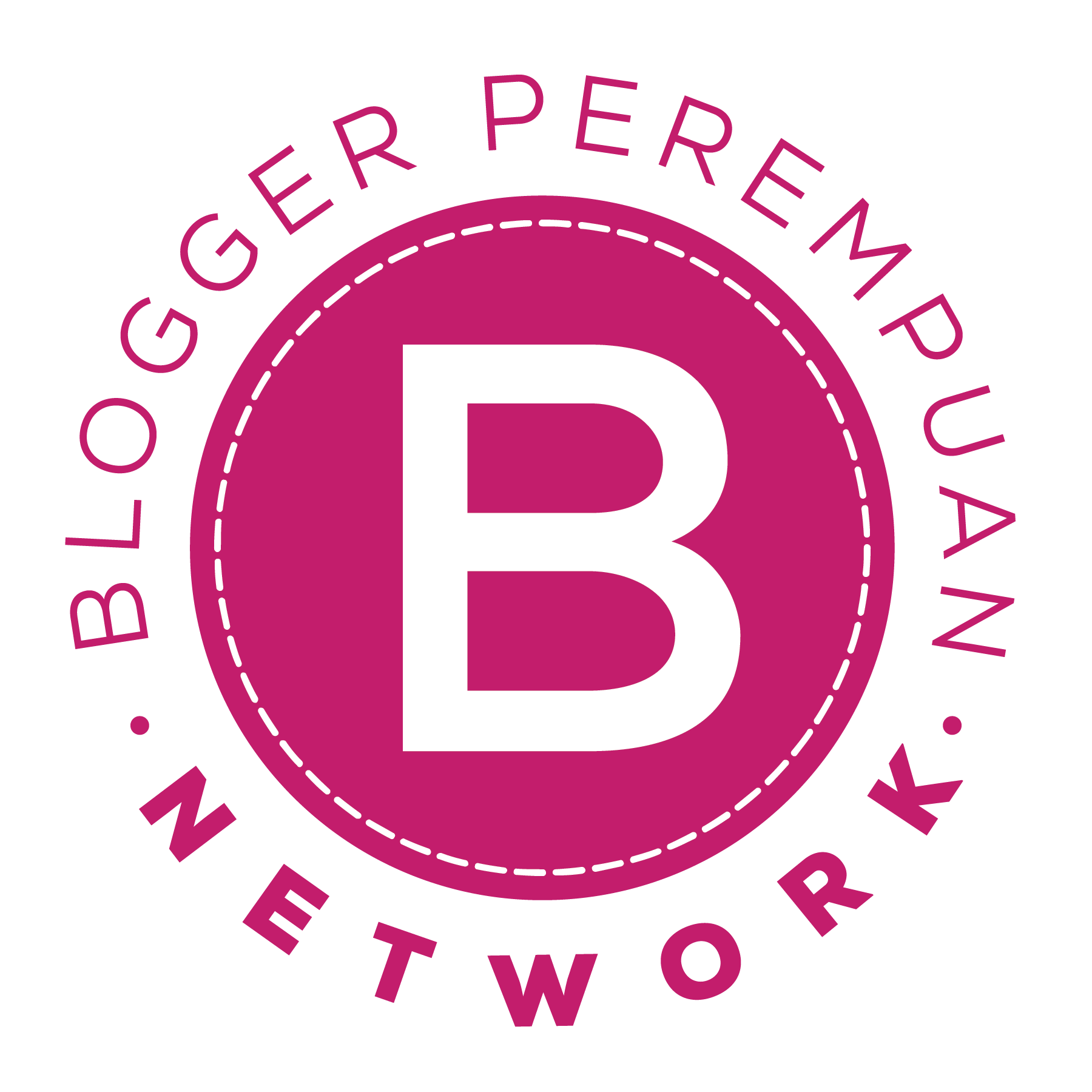
Duh merinding bacanya, saking relatednya dengan kondisi sekarang,
BalasHapusNovel 'hujan' ini berkaitan dengan kegelisahan, ya? Kalo dipikir-pikir, perubahan itu pun mungkin disebabkan oleh rasa takut, kegelisahan (khawatir) atau kebingungam. Alami banget sih, asal kadarnya gak berlebih. Seperti yg diisyaratkan Esok di novel ini. Esok yg (mungkin) berarti harapan..
BalasHapusNovel ini aku DAPAT di IBF tahun 2018. Sampe sekarang belum kubaca. Jadi penasaran nih mb Rindang. Cuman gegara aku ngga ngeh awal2nya itu bingung bacanya. Jadinya kutinggal deh. Otw deh habis niii
BalasHapusBerisi banget ya kalau Bang Darwis nulis novel ini. Walaupun aku nggak megang novelnya, tapi baca review ini aja udah ngerasa banget betapa novelnya itu "daging" banget. Nggak cuma "kulit" aja.
BalasHapussalah satu novel paling berkesan. Hujan mengajarkan banyak hal, terutama tentang keseimbangan. baik yang duniawi maupun yang tidak terlihat dan tersentuh.
BalasHapusSaya belum pernah baca Hujan. Relasi perenungan antara kisah di novel Hujan dan pandemi covid yang Mbak Rindang tulis membuat saya merenung juga. :)
BalasHapusKok bisa nyambung ya?
BalasHapusI think the pandemi , this Allah love for us and in the word
BalasHapus